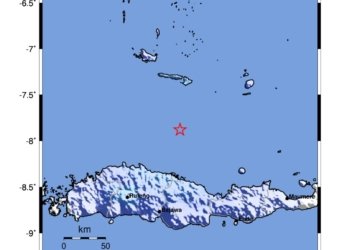Oleh Alfred Tuname*
Sebuah jabatan memiliki harga. Karena itu, untuk memiliki sebuah jabatan dibutuhkan kerja keras, kalau bukan pengorbanan. Apalagi untuk mendapatkan sebuah jabatan strategis, dibutuhkan kiat-kiat strategis untuk mencapainya.
Setiap orang punya kiat-kiatnya sendiri untuk mencapai jabatan tertentu. Ada yang legal, ada juga yang “ilegal”. Legal itu bersifat terbuka; ilegal itu biasanya tertutup. Cara legal membutuhkan kemampuan intelektual dan integritas; cara “ilegal” membutuhkan kemampuan lobi dan uang, kalau bukan nepotisme.
Penangkapan Romahurmuzy atau disapa Romi yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (pada tanggal 15 Maret 2019) tidak lepas dari aksi “ilegal” Romi untuk memuluskan jabatan seseorang di lingkup Kementerian Agama. Asal ada uang dan sedikit lobi, Romi bisa menjanjikan seseorang untuk mendapatkan jabatan. Itulah salah satu kasus “harga sebuah jabatan”. Sebuah anomali memang, tetapi itu terjadi.
Kalau orang Prancis bilang, “noblesse oblige”. Posisi atau jabatan menghendaki rasa tanggung jawab. Kekuasaan, kehormatan, kekayaan, etc, equal dengan tanggung jawab. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap bawahan atau masyarakat.
Kalau posisi atau jabatannya diperoleh dengan cara yang “legal”, seseorang akan melihat jabatan sebagai amanah. Kata itu berasal dari kata “amuna” yang bermakna tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan (Republika, 17/2/2016). Jadi, sebagai amanah, jabatan itu hanyalah titipan yang seharusnya dipergunakan secara jujur untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi.
Soalnya adalah kepentingan pribadi lebih besar manakala jabatan itu diperoleh. Tesis polisi Inggris, Lord Acton, pada abad 19 mendekati kenyataan. “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Semakin tinggi jabatan perilaku busuknya semakin tinggi. Itu terjadi karena kepentingan pribadi yang begitu tinggi.
Kepentingan pribadi itu tentu bukan hanya harta, tetapi soal status, prestise dan privilese. Tetapi karena status, prestise dan privilese itu sudah menjadi barang dagangan, diperlukan sedikit “biaya” untuk merawatnya. Jika salah merawatnya, maka semua itu akan hilang. Yang jelas, jabatan itu sebuah “accessible status”. Setiap orang berkemungkinan meraih sebuah posisi.
Jika berkaca pada kasus Romi, maka manuver “ilegal”-nya tentu berkaitan dengan merawat posisinya sebagai Ketua Umum Partai PPP. Bahwa ia butuh dana dan dukungan siapa saja yang dibantunya untuk melanggengkan posisinya. Dengan pengaruh, ia mendapatkan loyalis dan fulus untuk memuluskan kepentingan pribadinya.
Romi adalah satu dari seribu satu kasus “jual-beli” jabatan di negeri ini. Ada begitu banyak kasus seperti itu terjadi, baik yang sudah terjerat hukum maupun yang lolos dari jeratan hukum. Di daerah, “jual-beli” jabatan menjadi hal yang cukup lumrah. Masyarakat sudah tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Atau semacam sikap fetishist disavowal: I know very well, but… Tetapi semua itu terjadi.
Pertama, Bupati Klaten, Sri Hartini divonis hukum 11 tahun penjara karena perbuatan jual-beli jabatan di Pemkab Klaten pada tahun 2017. Kedua, Bupati Taufiqurrahman menjadi pesakitan KPK setelah melakukan perbuatan jual-beli jabatan di Pemkab Nganjuk pada tahun 2017. Ketiga, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, ditangkap KPK karena menerima suap dalam kasus jual-beli jabatan pada tahun 2018.
Ketiga kasus jual-beli jabatan tersebut terjaring OTT KPK. Tanpa KPK, Bupati dan para “position seekers” tersebut akan melenggang bebas memanfaatkan posisinya. Di lingkungan Pemda, semua ASN pasti sama-sama tahu. Desas-desus perihal “jual-beli” jabatan pasti terdengar jelas di telinga. Hanya saja, tak ada yang berani buka suara. Yang ada hanya reaksi-reaksi kekecewaan atau tercelup dalam rasa galau akut.
Semua reaksi itu hanya empty gesture atau gerakan kosong ASN yang tak berdampak. Tanpa dana dan lobi, mereka tak mendapat apa-apa. Tesisnya, pada pemerintahan yang korup, integritas dan intelektualitas tidak berarti apa-apa; kinerja dan disiplin memiliki nilai yang sama dengan nol (besar). Karena jabatan sudah sama dengan “barang” (komoditas).
Tetapi pada pemerintahan yang lahir dari proses politik yang bersih, KPK hadir hanya sebagai “watchdog”, tidak menggigit. “Jual beli” jabatan pun tidak terjadi. Cara pandangnya, jabatan itu amanah, bukan hadiah.
Sebab, apalah arti sebuah jabatan apabila orang yang menempati posisi itu tidak bekerja sesuai dengan visi-misi pemerintah (daerah); apalah arti sebuah jabatan apabila orang yang menempati posisi itu kapabel dan tidak loyal terhadap perintah dan kebijakan pemimpin.
Jabatan bisa dicabut dari seseorang apabila posisinya tidak bermanfaat bagi publik dan tidak sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan itu berfungsi sebagai “skrup” yang dipasang untuk menguatkan bangunan pemerintahan yang melayani publik. “Skrup” itu bukan dibeli, tetapi dicari karena kekuatan dan ketahanan (:“antikarat”).
Jadi, harga sebuah jabatan ada pada manfaatnya bagi kepentingan banyak orang. Di situ ada integritas dan kualitas pejabatnya. “Tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian”, kata Gus Dus. Tetapi kalau ada seseorang yang mati-matian menginginkan sebuah jabatan, dialah yang dibuang jauh-jauh. Dialah “skrup” yang karat itu.
*) Penulis dan Esais